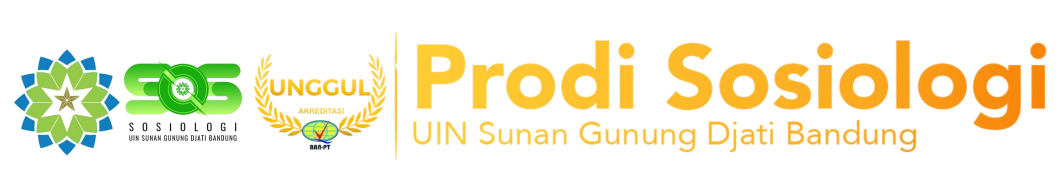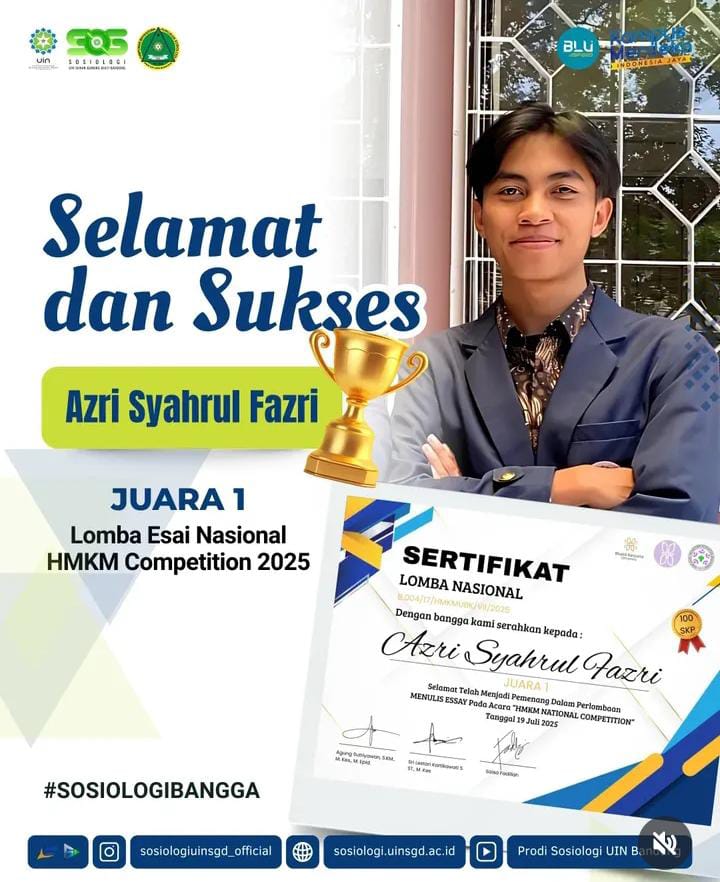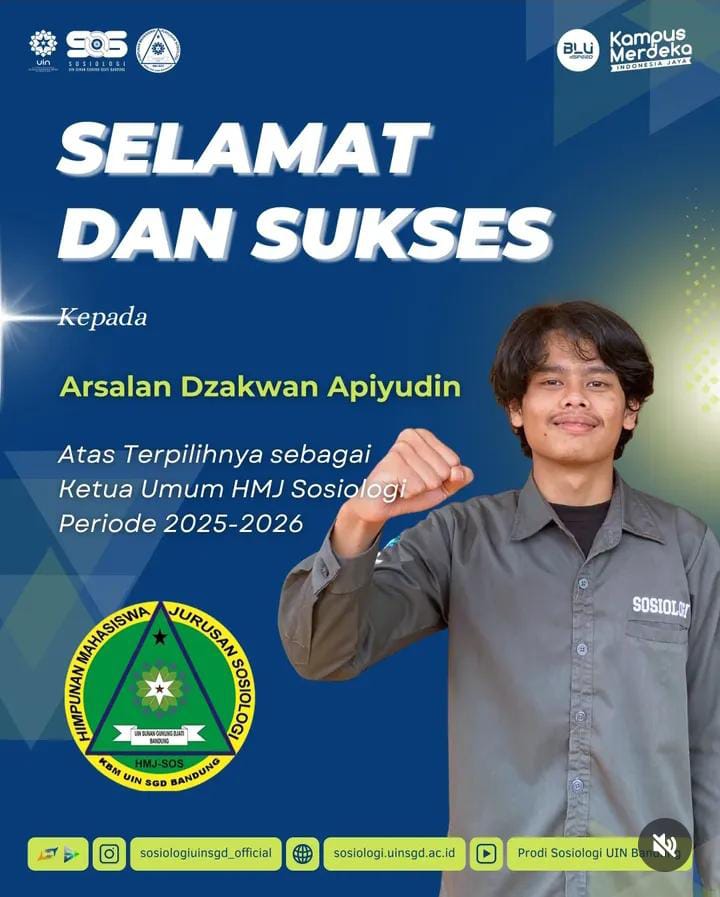Perang antara Iran dan Israel bukan sekadar konflik geopolitik, melainkan juga fenomena sosial yang dapat dianalisis melalui berbagai perspektif sosiologi. Dengan memahami bagaimana sosiologi memandang perang, kita dapat melihat konflik ini tidak hanya sebagai kehancuran semata, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih luas.
1. Fungsionalisme: Perang sebagai Instrumen Sosial
Dari sudut pandang fungsionalisme, perang memiliki fungsi sosial tersendiri. Fungsionalisme memandang setiap perilaku dan lembaga dalam masyarakat—termasuk perang—sebagai sesuatu yang dapat memberikan kontribusi terhadap keteraturan sosial.
Robert E. Park dalam tulisannya “Fungsi Sosial Perang” (1941) menjelaskan bahwa meskipun perang menyebabkan penderitaan, ia juga memiliki kegunaan tersembunyi bagi masyarakat. Pertama, perang dapat menyelesaikan konflik besar antarnegara, seperti perselisihan batas wilayah atau perbedaan ideologi. Pemenang perang umumnya membawa hasil akhir terhadap konflik tersebut.
Kedua, perang meningkatkan solidaritas sosial. Di tengah ancaman eksternal, masyarakat menjadi lebih kompak, bersatu dalam semangat patriotisme dan nasionalisme untuk menghadapi musuh bersama. Rasa identitas kolektif ini seringkali lebih kuat daripada masa-masa damai.
Ketiga, pengembangan senjata dan strategi perang sering kali mendorong inovasi teknologi. Internet, misalnya, awalnya dikembangkan dari riset pertahanan. Dengan kata lain, perang bisa menjadi katalis bagi kemajuan ilmiah.
2. Perspektif Konflik: Perang sebagai Perebutan Kekuasaan
Berbeda dengan fungsionalisme, perspektif konflik melihat perang sebagai konsekuensi dari ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya. Menurut teori ini, konflik seperti perang Iran-Israel muncul karena adanya perebutan pengaruh, kekayaan, atau kendali atas kawasan strategis.
Perang juga dipahami sebagai alat untuk mempertahankan atau memperbesar kekuasaan kelompok elit tertentu. Negara-negara sering kali mengalokasikan anggaran besar untuk militer karena adanya kolaborasi antara politisi, produsen senjata, dan pemimpin pertahanan. Ini menciptakan jejaring kepentingan yang saling menguntungkan, bahkan di tengah penderitaan rakyat.
Contohnya bisa dilihat dalam konteks Ukraina pascaperang. Ketika negara tersebut membangun kembali, negara-negara Barat memperoleh keuntungan melalui proyek pembangunan dan ekspansi ekonomi. Perang, dalam kacamata ini, adalah medan kompetisi kapitalisme global.
3. Interaksionisme Simbolik: Makna Simbolik Perang
Sementara itu, perspektif interaksionis simbolik menyoroti bagaimana simbol dan makna sosial dibentuk selama perang. Simbol seperti bendera, lagu kebangsaan, atau slogan digunakan untuk menguatkan rasa patriotisme dan solidaritas.
Dalam konteks perang Iran-Israel, para pemimpin sering kali menggunakan simbol-simbol nasionalis untuk membentuk opini publik dan menumbuhkan semangat juang. Masyarakat didorong untuk memaknai konflik bukan sekadar benturan kekuatan, melainkan sebagai perjuangan suci atau pertahanan harga diri bangsa. Dengan demikian, makna perang dibentuk melalui komunikasi simbolik yang berulang dan intens.
Penutup: Sosiologi Membantu Kita Memahami Dimensi Sosial Perang
Perang bukan hanya soal senjata dan strategi, tetapi juga soal bagaimana masyarakat memaknainya, meresponsnya, dan membentuk solidaritas atau konflik karenanya. Melalui lensa fungsionalisme, konflik, dan interaksionisme simbolik, sosiologi memberikan wawasan yang lebih dalam tentang realitas perang Iran dan Israel. Kita diajak untuk tidak hanya melihat akibatnya, tetapi juga memahami sebab-sebab dan makna sosial yang menyertainya.
Penulis: Dr. Dede Syarif, Dosen S1 Sosiologi dan Ketua Magister Sosiologi
Sumber: https://perspektifsosiologi.com/2025/06/23/melihat-perang-iran-vs-israel-dari-perspektif-sosiologi/